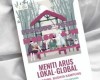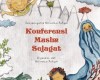Afirmasi Kota Ramah Lansia #1

Urgensi Afirmasi Lansia. Mikul dhuwur mendhem jero : adalah salah satu filosofi masyarakat Jawa yang mendalam menjadi pondasi penting bagi upaya memulai diskursus terkait Lanjut Usia/Lansia dimana Lansia merupakan situasi yang normal. Setiap kita akan mengalami situasi tersebut sebagai sebuah siklus yang berkonsekuensi pada perilaku yang juga berubah, baik secara medis, psikologis maupun sosiologis. Oleh karenanya, Lansia atau orang yang lebih tua, yang mengacu pada semua orang yang berusia 60 atau di atasnya (≥ 60) dan didefinisikan menurut berbagai karakteristik termasuk: usia kronologis, perubahan pada peran sosial dan perubahan pada kemampuan fungsional. Situasi yang spesial karena perubahan tersebut bisa dimaknai sebagai perubahan secara fisiologis berupa berkurangnya kemampuan fisik dalam keseharian seseorang.
Siklus situasi Lanjut Usia merupakan proses dari tumbuh kembang yang akan dijalami setiap individu, yang ditandai dengan penurunan kemampuan tubuh dalam beradaptasi dengan lingkungan. Kondisi tersebut bisa diindikasi dengan perubahan dalam wujud penurunan kondisi seseorang dalam fungsi kognitif dan psikomotor. Pada fungsi kognisi, Lansia akan mengalami reaksi yang melambat untuk proses memahami sesuatu, persepsi, pengertian, perhatian dan proses belajar. Dan pada fungsi psikomotor maka mengalami pengurangan dalam kemampuan untuk mengkoordinasi gerakan maupun tindakan terkait aktivitas fisik. Pada kondisi tersebut seorang individu yang memasuki fase Lansia sangat rentan dalam kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan baik pada level individu, kelompok maupun lingkungan sosial, baik dalam jangka pendek maupun panjang (WHO, 2011). Kondisi tersebut tentu saja berimplikasi pada banyak hal : demografi Lansia yang mengalami kenaikan secara intens idealnya bisa dimaknai sebagai bagian dari agenda pembangunan yang inklusif.
Upaya peningkatan Lansia menunjukkan sisi lain keberhasilan program-program terkait layanan kesehatan beserta segala turunannya yang telah dicanangkan pemerintah selama ini. Kerangka penting untuk memberi ruang bagi upaya tersebut adalah memahami kondisi Lansia dan kebutuhan yang tidak bisa dilepaskan dengan kondisi kelanjutusian yang ada. Baik kebutuhan yang bersifat fisik layaknya pangan, sandang, papan, aksesibilitas dan fasilitas penunjang kesehatan maupun kebutuhan yang bersifat non fisik seperti agenda sosial, organisasi sesama maupun lembaga yang menopang keberadaan Lansia. Dengan pemenuhan kebutuhan tersebut harapannya rasa aman, cinta dan kasih sayang bisa disediakan sehingga Lansia bisa melaksanakan peran dalam masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi sosialnya.
Rendah dan minimnya daya topang pada keberadaan Lansia di satu sisi dan kenaikan jumlah Lansia di sisi lain membuat eksistensi Lansia sejauh ini dimaknai sebagai beban baik bagi individu, keluarga maupun lingkungan. Kondisi tersebut berimbas pada streotipe Lansia karena banyaknya keterbatasan baik secara fisik, kesehatan, maupun secara ekonomi. Situasi tersebut berujung pada tertutupnya ruang bagi kemungkinan proses nan dinamis bagi Lansia. Menjadi Lansia seperti menghilangkan kesempatan untuk tetap produktif secara fisik maupun non fisik dan tetap bisa berkontribusi bagi lingkungan sosialnya. Pemenuhan kesejahteraan bagi Lansia tidak hanya menempatkan Lansia sebagai obyek dalam program pemberdayaan namun memungkinkan proses lebih jauh yaitu Lansia hadir sebagai subyek dalam konteks pemberdayaan yang luas. Merujuk pada catatan Badan Pusat Statistik yang menyusun proyeksi pada 2045, Indonesia akan memiliki sekitar 63,31 juta penduduk lanjut usia atau mencapai hampir 20 % populasi.
Setidaknya, tercatat selama kurun waktu 1971-2018, persentase penduduk Lansia Indonesia meningkat sekitar dua kali lipat. Kondisi tersebut tentu saja berkaitan dengan meningkatnya usia harapan hidup, ketika usia harapan hidup pada tahun 1990 ada pada angka 63,6 tahun menjadi 71,7 pada tahun 2016. Berdasarkan data proyeksi penduduk, diperkirakan tahun 2017 terdapat 23,66 juta jiwa penduduk lansia di Indonesia (9,03%). Diprediksi jumlah penduduk Lansia tahun 2020 (27,08 juta), tahun 2025 (33,69 juta), tahun 2030 (40,95 juta) dan tahun 2035 (48,19 juta). Sehingga, suatu negara dikatakan berstruktur tua jika mempunyai populasi Lansia di atas 7 % (Kemenkes, 2017) dan tercatat setidaknya dari 21,7 juta jiwa diatas 60 tahun tersebut, sekitar 45% berada di rumah tangga dengan status sosial ekonomi 40% terendah (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2017).
BPS menunjukkan realita Lansia sampai dengan tahun 2017, persentase penduduk Lansia mencapai 9,03% dari keseluruhan penduduk. Data terakhir menunjukkan bahwa distribusi mayoritas provinsi yang berstruktur penduduk tua, terdapat pada 19 provinsi (55,88%) di Indonesia yang memiliki struktur penduduk tua. Tiga provinsi dengan persentase Lansia terbesar adalah DI Yogyakarta (13,81%), Jawa Tengah (12,59) dan Jawa Timur (12,25%). Sementara itu, tiga Provinsi dengan persentase lansia terkecil adalah Papua (3,20%), Papua Barat (4,33%) dan Kepulauan Riau (4,35%). Sedangkan 2018, Badan Pusat Statistik juga merilis angka Lansia yang mengalami kenaikan mencapai 9,27% atau sekitar 24,49 juta orang, dengan dominasi oleh Lansia Muda (kelompok umur 60-69 tahun) yang persentasenya mencapai 63,39%, sisanya adalah Lansia Madya (kelompok umur 70-79 tahun) sebesar 27,92%, dan Lansia Tua (kelompok umur 80+) sebesar 8,69%, trend kuantitatif yang secara signifikan mengalami kenaikan (Statistik Lanjut Usia, BPS 2018).
Mendorong hadirnya kebijakan khusus yang bisa mengafirmasi Lansia baik dalam konteks nasional serta kebijakan maupun implementasi ditingkat lokal menjadi sangat penting. Kebiakan tersebut hadir untuk memberi jaminan bagi upaya mewujudkan pemenuhan hak dan upaya merealisasikan kesejahteraan bagi Lansia. Mengingat makin besarnya proporsi penduduk Lansia maka kebijakan khusus Lansia dengan maksud untuk: (i) menghadapi stereotip negatif dan mempromosikan penerimaan penuaan sebagai bagian dari hidup normal; (ii) mengidentifikasi dan mengatasi diskriminasi yang berkaitan dengan usia di semua bidang kebijakan dan regulasi; (iii) memberikan ruang-ruang partisipasi dalam konteks pembangunan; (iv) memfasilitasi perumusan kebijakan yang mempromosikan dan penguatan kemampuan daripada ketergantungan, dengan memastikan bahwa kriteria untuk akses ke layanan pada promosi kesehatan dan inklusi sosial daripada pada penanganan penyakit maupun penurunan fungsional/degenerative.
Kerangka kebijakan khusus Lanjut Usia, pada konteks makro dapat menjadi rujukan untuk mempromosikan hubungan yang harmonis antara pembangunan dan perubahan demografis, paduan perlindungan sosial dan memastikan terakomodasinya populasi Lansia dalam kebijakan kesehatan. Sehingga kebijakan perawatan jangka panjang dalam berbagai situasi dan kondisi yang berbeda‐beda inklusif bagi bagi Lansia. Dan dalam konteks yang lebih mikro ditingkat teknis Pemerintah Daerah setidaknya menjadi panduan untuk mendorong komitmen dan mempromosikan kebijakan, program dan anggaran bagi implementasi kebijakan bagi Lansia. Mengingat kewenangan daerah yang otonom dan sebaran populasi Lansia yang terdistribusi diberbagai wilayah mesti terjangkau secara langsung dengan layanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah setempat. #KotaSolo #Lansia
Oleh Akhmad Ramdhon
Catat refleksi bersama Elsam Jakarta
Catat refleksi bersama Elsam Jakarta