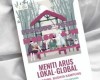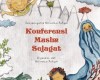2019, Solo, Kota Kreatif

Kota Solo sudah dua kali mengajukan proposal agar diterima kedalam Jaringan Kota-Kota Kreatif UNESCO. Usaha pertama dirintis sejak tahun 2013 dengan dukungan penuh Bekraf. Saat itu terdapat 4 kota yang diusulkan oleh Bekraf untuk memproses pengajuan proposal Kota Kreatif. Kota Solo dan Bandung diusulkan menjadi Kota Desain. Sedangkan kota Yogja dan Pekalongan diusulkan menjadi kota kerajinan dan kesenian rakyat.
Keempat proposal kota tersebut lantas diajukan. Pada tahun 2014, Pekalongan diterima menjadi bagian jaringan Kota Kreatif. Setahun berikutnya Bandung juga diterima. Tetapi kota Solo dinyatakan gagal, secara resmi pengumuman kegagalan diterima pada tahun 2017. Pada tahun 2019 ini, kota Solo kembali mengajukan proposal Kota Kreatif. Sedikit berbeda, kali ini kota Solo mengajukan diri menjadi Kota Kerajinan dan Kesenian Rakyat. Hailnya, pada Oktober kemaren kota Solo kembali gagal masuk ke dalam jaringan Kota Kreatif. Kota ‘kreatif’ (dengan huruf ‘k’ kecil)
Seandainya proposal tersebut berhasilpun, apakah lantas Solo akan menjadi kota yang benar-benar kreatif? Jawabannya: TIDAK. Kota Kreatif (dengan ‘K’ besar) sesungguhnya justru punya potensi merusak sebuah kota. Konsep Kota Kreatif ini selalu diikuti sederetan kebijakan yang kurang lebih sama. Pembangunan infrastruktur ekonomi kreatif berskala besar, beutifikasi wajah perkotaan, pemberian fasilitas dan insentif kepada individu kreatif (seniman, desainer, arsitek, dll) dalam bentuk grant proyek, kampanye branding kota secara massif, dll. Semuanya atas nama untuk menegaskan identitas kota yang ‘kreatif’.
Logika umum yang digenggam erat para inisiator Kota Kreatif juga selalu sama. Bahwa sebuah kota yang kreatif akan menstimulasi perekonomian kota lebih cepat berkembang. Dengan meningkatkan daya tarik kota, berujung kepada meningkatnya peluang investasi bisnis maupun geliat pariwisata. Sebagai jargon pelengkap, Kota Kreatif juga mendorong terwujudnya inklusi sosial, partisipasi budaya, pengurangan kemiskinan, dan secara umum mewujudkan kota yang lebih layak dihuni. Itulah utopia para penggagas Kota Kreatif yang tentunya mudah mengelabui banyak pemerintah kota.
Tapi realitanya, dalam upaya menjadi kreatif tersebut, kota justru menjauh dari upaya peningkatan kreativitas dan kemampuan inovasi warganya. Kota Kreatif justru menjauh dari visi mereka sendiri. Dari pada menumbuhkan kualitas kehidupan urban, Kota Kreatif justru mengekalkan masalah-masalah klasik perkotaan, seperti kesenjangan ekonomi, ekslusi sosial, pelapukan budaya, dan pada beberapa kasus kerusuhan politik. Misalnya, dalam praktik privatisasi ruang publik, alih fungsi peruntukan ruang publik, regenerasi kawasan kota yang dianggap ‘kumuh’, dll, berujung pada penggusuran eksistensi ekonomi, sosial, dan budaya warga.
Selain merusak, kebijakan retoris Kota Kreatif tersebut juga tidak ada dampaknya terhadap peningkatan kreativitas individu warga. Kebijakan tersebut di desain sebagai sebuah program replikasi, mengglobal, dan mereproduksi homogenitas lanskap urban di seluruh dunia. Bisa dikatakan Kota Kreatif justru telah menghancurkan konsep ‘kreatif’ yang bersendi kepada otentisitas dan keberagaman. Semua diambil alih, diseragamkan, dikemas agar efisien menjadi paket wisata untuk dijual kepada publik dunia.
Lebih jauh kerusakan yang ditimbulkan dari Kota Kreatif adalah pengambil alihan praktik kreatif warga yang organic dan jujur. Praktik jujur tersebut terdapat dalam – misalnya- praktik pengambil alihan, pelanggaran, intervensi, subversi, perlawanan, aktivisme, dan eksperimen. Oleh Kota Kreatif, bentuk-bentuk aksi tersebut sengaja di beri makna baru yang cenderung negative. Direduksi. Atau dalam bentuk yang lebih bahaya, aksi-aksi itu justru dikooptasi dan dikapitalisasi.
Bentuk-bentuk aksi kreatif nan organic tadi sesungguhnya adalah spirit dimana kata ‘kota kreatif’ (dengan huruf ‘k’ kecil) seharusnya dialamatkan. Aksi-aksi tersebut bisa kita lihat dalam praktik keseharian urban sub-kultur, misalnya scene musik lokal, supporter bola, skateboard circle, street art, kelompok kesenian kampung, urban farming, dan lainnya.
Dalam praktik-praktik kreatif urban sub-kultur tersebut sifat pengorganisasiannya lebih cair, menjalar (berjejaring), dan bersifat eksperimental. Warga dengan spontan merespon lingkungan sekitarnya untuk menumpahkan ekspresi, kemarahan, kecemasan, kecintaan, kegembiraan dan emosi lain terhadap situasi kota. Praktik-praktik spontan tersebut memberi jaminan kabaruan. keberagaman, keunikan, dan kesegaran, yang semua itu adalah hakikat sesungguhnya dari energi kreatif manusia. Para pelakuknya merupakan individu atau kelompok yang otonom, bebas dari dorongan ekonomis, arahan pemerintah kota, atau motivasi politis apapun.Merekalah sejatinya komponen utama kota kreatif. Warga yang aktif, sadar, dan awas atas kondisi kotanya. Bukan warga yang pasif sekedar menjadi konsumen yang terpana dengan konsep Kota Kreatif.
Walaupun Kota Kreatif berusaha ‘menjinakkan’ aksi kreatif warga yang organic tersebut, akan tetapi tidak serta merta aksi-aksi tersebut diberangus. Akar etos kapitalisme dalam konsep Kota Kreatif terbiasa menggunakan strategi komodifikasi aksi ‘perlawanan’. Terlebih Kota Kreatif juga membutuhkan ‘wajah’ yang unik, beda, artsy, agar laku dijual. Oleh karena itu, tidak mengherankan ketika pemerintah kota dan para pelaku industri wisata beramai-ramai mensponsori aktivitas kreatif (misalnya: mural, street art, gig music, dll). Seolah mengafirmasi semangat perlawanannya, padahal tidak lebih dari upaya komersialisasi perlawanan untuk dijual sebagai komoditas.
Celakanya, yang terjadi kemudian, aksi komodifikasi perlawanan itu dilakukan hampir oleh seluruh Kota Kreatif. Karena itulah rumus baku yang mereka terima dari para penggagasnya. Akibatnya kembali terjadi replikasi dan homogenitas wajah kota. Kita bisa saksikan betapa proyek mural, festival anak muda, festival budaya, festival jalanan, menjadi fenomena umum yang mewarnai wajah kota-kota di Indonesia. Tidak ada lagi gagasan maupun bentuk-bentuk segar yang muncul. Yang ada adalah pengulangan - misalnya event budaya- dengan rumus baku, standart Kota Kreatif, yang tak lagi kreatif.
Maka sudah seharusnya kita tidak perlu peduli dengan jargon Kota Kreatif. Abaikan saja. Parameter kreativitas tidak layak ditentukan dengan pertimbangan peningkatan ekonomi oleh pemerintah kota dan pengusaha. Warga kota secara aktif berhak membangun konsepsi ‘kreativitas’ mereka. Hak atas kota sejatinya termasuk pula hak warganya untuk menyusun wajah kota mereka.
Maka mari, bebaskan ekspresi urban kita. Rebut kembali ruang-ruang yang selama ini dikooptasi oleh Kota Kreatif. Semarakkan aksi-aksi spontanitas komunal warga. Saling bersolidaritas, saling bantu mengembangkan secara mandiri bentuk-bentuk ekspresi kreatif yang membumi. Selenggarakan festival-festival kesenian, puisi, teater, musik, kethoprak, dll di kampus, dan di kampung sekitar kita. Festival lokal oleh warga dan untuk warga. Tidak perlu jargon ‘internasional’ kalau hanya dikooptasi oleh pemkot dan pengusaha. Tunjukan kepada penguasa kota bahwa warga berdaya menentukan apa itu kreativitas. Kota kreatif pada akhirnya adalah kota yang aktif oleh kreativitas kewargaan. Sebuah kota aktivisme. Kota yang subversif.
Oleh Andi Setiawan/FSRD UNS
Disampaikan pada sesi Pidato Akhir Tahun 2019
Disampaikan pada sesi Pidato Akhir Tahun 2019