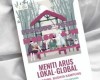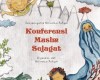Afirmasi Kota Ramah Lansia #2

Kerangka Kebijakan Lansia. Berdasarkan kondisi kerentanan dan sumbangan jangka panjang keberadaan Lansia maka menjadi penting memahami konteks bagi kebijakan yang semakin inklusif, menjamin adanya perlindungan dan komitmen mewujudkan kesejahteraan. Di Indonesia sendiri kebijakan khusus yang ditujukan untuk memberikan afirmasi bagi Lansia sesungguhnya bukan hal baru. Mengemuka pada tahun 1965 dengan keluarnya UU No. 4/1965 tentang Pemberian Bantuan Penghidupan Orang Jompo. Selama pemerintahan Orde Baru, kewenangan penanganan terhadap Lansia dikelola secara khusus oleh Departemen Sosial, dengan sejumlah program baik dari pusat maupun di tingkat daerah. Pendekatan struktural dan rehabilitasi menjadi pola pembinaan yang sangat dominan bila harus dibandingkan dengan orientasi pemberdayaan Lansia maupun pra Lansia.
Upaya pemenuhan hak menjadi kewajiban konstitusi, dimana kewajiban tersebut meliputi perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak‐hak Lansia; termasuk menjamin tidak adanya kebijakan yang diskriminatif. Pasal 28 H ayat (2) UUD 1945 menjadi landasan yang kuat bagi semua golongan warga negara untuk bebas dari diskriminasi sistematik dan struktural dalam berbagai aspek kehidupan. Pasal tersebut mengakui kerentanan sebuah kelompok harus dilindungi dengan menciptakan kebijakan yang bersifat khusus (affirmative action) untuk mencegah dan menghapus kondisi diskriminatif yang merugikan kelompok masyarakat tertentu. Penegasan upaya pemulihan atas situasi diskriminatif yang terjadi juga terdapat pada Pasal 5 (3) UU No. 39/1999 tentang HAM yang menyatakan bahwa, setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.
Terobosan besar sekaligus pembaruan kebijakan khusus bagi Lansia hadir dengan keluarnya UU No. 13/1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Lanjut Usia didefinikan seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun (enam puluh) tahun keatas. Dan dikategorikan dalam Lanjut Usia Potensial adalah lanjut usia yang masih mampumelakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa. Serta Lanjut Usia Tidak Potensial adalah Lanjut Usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain. Kebijakan khusus sebagai upaya untuk meningkatan kesejahteraan sosial Lansia (Pasal 3-4) diarahkan pada upaya pemberdayaan sehingga berperan dalam kegiatan pembangunan dengan memperhatikan fungsi, kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia, dan kondisi fisiknya. Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bertujuan untuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif, kemandirian dan kesejahteraannya serta melaksanakan fungsi sosialnya (Pasal 9-10).
Komitmen untuk memberi penghormatan dan penghargaan menurut ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU Kesejahteraan Lansia, setiap Lansia berhak untuk mendapatkan (a) pelayanan keagamaan dan mental spiritual, (b) pelayanan kesehatan, (c) pelayanan kesempatan kerja, (d) pelayanan pendidikan dan pelatihan, (e) kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum, (f) kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum, (g) perlindungan sosial, dan (h) bantuan sosial. Kondisi tersebut berlaku untuk semua kategori Lansia, kecuali Pasal 11 (c) bahkan memberi perbedaan kesempatan bagi Lansia dengan usia potensial. Dengan memberi memberi peluang untuk mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimilikinya, baik pada pada sektor formal dan non formal (Pasal 15).
Peraturan Pemerintah No 43/2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia jadi upaya untuk menindaklanjuti ketentuan UU No. 13/1998, terkait teknis beragam upaya peningkatan layanan kesejahteraan bagi Lansia. Adapun yang ada meliputi, pelayanan keagamaan dan mental spiritual berupa bimbingan beragama dan pembangunan sarana ibadah dengan penyediaan aksesibilitas bagi Lanjut Usia. Sedangkan pelayanan kesehatan selain memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan agar kondisi fisik, mental, dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar. Lewat penyuluhan dan penyebar luasan informasi kesehatan, upaya penyembuhan (kuratif), pengembangan lembaga perawatan hingga diberikan keringanan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan. Sesuai Pasal 138 UU 36/2009 tentang Kesehatan menegaskan bagi Lanjut Usia upaya kesehatan harus ditujukan untuk menjaga agar tetap hidup sehat dan produktif secara sosial maupun ekonomis sesuai dengan martabat kemanusiaan.
Ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan memfasilitasi kelompok lanjut usia untuk dapat tetap hidup mandiri dan produktif secara sosial dan ekonomis. Sehingga bagi Lansia yang potensial juga mempunyia pelayanan kesempatan kerja bagi dalam bentuk memberi peluang untuk mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimilikinya pada sektor formal dan non formal. Untuk itu, dukungan pelayanan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan, dan pengalaman lanjut usia potensial sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Mengingat jumlah Lansia diperkirakan 21,7 juta jiwa atau 8,5% total penduduk Indonesia (Susenas, 2015) maka sekitar 45% berada di rumah tangga dengan status sosial ekonomi 40% terendah (TNP2K, 2017).
Kebutuhan lain bagi Lansia yang diatur Peraturan Pemerintah No 43/2004 yaitu pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum termasuk layanan kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan, keringanan biaya; perjalanan, maupun penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus. Terkait pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan sarana dan prasarana umum dimaksudkan untuk memberikan aksesibilitas tertutama di tempat-tempat umum yang dapat menghambat mobilitas lanjut usia. Adapun penyediaan aksesibilitas bagilanjut usia pada sarana dan prasarana umum dapat berbentuk fisik berupa aksesilbitas dan non fisik berupa informasi maupun layanan khusus bagi pemenuhan kebutuhan mobilitas Lansia.
Komitmen Pemerintah dalam konteks Lansia yang mempunyai kekhususan berupa pemberian perlindungan sosial untuk memberikan pelayanan bagi lanjut usia tidak potensial yang diselenggarakan oleh lembaga terkait. Dimana skema rehabilitasi sosial Lanjut Usia harus memperhatikan prinsip mengutamakan fungsi keluarga dan lingkungannya, nondiskriminatif dan imparsial, serta pelayanan yang holistik, komprehensif, dan inklusif (Pasal 5, Permensos No 5/2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia). Sedangkan bantuan sosial diberikan kepada Lansia potensial bersifat tidak tetap, berbentuk material, finansial, fasilitas pelayanan dan informasi guna mendorong tumbuhnya kemandirian (Pasal 20 UU No. 13/1998). Skema Bansos (Subsidi Beras Sejahtera) Rastra bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan akses masyarakat miskin dan rentan melalui pemenuhan kebutuhan pangan pokok yang menjadi hak dasarnya. Sebesar 42,06 % rumah tangga lansia menerima bansos rastra dalam empat bulan terakhir pada tahun 2018 (Statistik Lanjut Usia, BPS 2018).
Bagian lain dari kebijakan khusus juga mengkoordinasikan peran dan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat luas. Sebab Peran masyarakat ditegaskan Pasal 22 (1-2) UU No. 13/1998, bahwa masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia dan bisa dilakukan perseorangan, keluarga, kelompok, masyakarat, organisasi sosial, dan/atau organisasi kemasyarakatan. Komitmen tersebut kemudian ditopang skema jaminan sosial lewat UU No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang memberi kerangka hukum untuk pemberian perlindungan bagi setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Dan memastikan setiap warga negara memiliki akses jaminan kesehatan dan jaminan sosial akibat berkurangnya pendapatan, menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, pensiun maupun memasuki fase lanjut usia (Pasal 18).
Selain peraturan perundang‐undangan khusus yang ditujukan untuk memberikan dukungan kesejahteraan sosial bagi Lansia, UU No. 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial juga menjadi sandaran penting percepatan program kesejahteraan, perlindungan, pemberdayaan dan jaminan sosial bagi Lansia (Pasal 6). Skema tersebut juga tidak bisa dilepaskan dengan komitmen (Pasal 138-139) UU 36/2009 tentang Kesehatan. Dimana penegasan upaya pemeliharaan kesehatan bagi Lansia harus ditujukan untuk menjaga agar tetap hidup sehat dan produktif secara sosial maupun ekonomis. dan Pemerintah wajib menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan memfasilitasi kelompok Lansia untuk dapat tetap hidup mandiri dan produktif secara sosial dan ekonomis. Jaminan implementasi kebijakan yang semakin inklusif bagi setiap warga negara dan secara khusus kelompok rentan.
Upaya mewujudkan kesejahteraan sosial secara teknis juga diatur dalam PP No. 39/2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Dimana upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi/Kota/Kabupaten, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial (Pasal 3). Jangkauan komitmen tersebut memprioritaskan, Pasal 2 (1-2) perseorangan, keluarga, kelompok; dan/atau masyarakat yang mempunyai .kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan. Dan memiliki kriteria masalah sosial seperti kemiskinan; ketelantaran; kecacatan; keterpencilan; ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku; korban bencana; dan/atau korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.
Kerangka kebijakan khusus yang mendukung upaya penyejahteraan Lansia, kemudian dikawal lewat mekanisme kerja Komisi Nasional Perlindungan Penduduk Lanjut Usia (Keppres No 52/2004). Komisi Nasional Lanjut Usia dapat bekerja sama dengan instansi Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, organisasi masyarakat, para ahli, hingga badan internasional. Termasuk didalamnya organisasi masyarakat yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial lanjut usia, perguruan tinggi dan dunia usaha lewat skema kemitraan. Dengan kepentingan menjadi pedoman dan untuk melakukan koordinasi pada level implementasi teknis oleh lembaga di bidang kesejahteraan sosial Lansia maupun lembaga kesejahteraan sosial, untuk membantu Lansia dalam memulihkan dan mengembangkan fungsi sosialnya. Baik didalam Panti maupun luar Panti, yang dikelola Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten hingga masyarakat (Permensos 19/2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia).
Sedangkan terkait layanan kesehatan bagi Lansia, diatur dalam Permenkes No. 67/2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Pusat Kesehatan Masyarakat. Dimana fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif. Kondisi tersebut sesuai dengan prinsip dalam mewujudkan Lanjut Usia sehat, mandiri, aktif dan produktif meliputi menjadi Lansia sehat adalah hak asasi setiap manusia, pelayanan kesehatan primer adalah ujung tombak, partisipasi dan layanan bagi Lansia secara lintas program dan lintas sektor serta dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kesetaraan gender (Permenkes No. 25 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Nasional Kesehatan Lanjut Usia Tahun 2016-2019).
Merujuk pada strategi Lansia sehat dari WHO 2013-2018 serta pada kebijakan pelayanan kesehatan lanjut usia yang komprehensif maka strategi nasional Rencana Aksi Nasional Kesehatan Lanjut Usia Tahun 2016-2019. Antara lain, memperkuat dasar hukum pelaksanaan pelayanan kesehatan, meningkatkan informasi, kuantitas serta kualitas fasilitas kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan. Kemudian membangun dan mengembangkan kemitraan dan jejaring pelaksanaan pelayanan kesehatan yang melibatkan lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, lembaga pendidikan, lembaga penelitian, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, media massa dan pihak terkait lainnya. Serta peningkatkan peran serta dan pemberdayaan keluarga, masyarakat, dalam upaya peningkatan kesehatan Lanjut Usia. Terakhir, adanya upaya peningkatkan peran serta Lansia dalam upaya peningkatan kesehatan keluarga dan masyarakat (Permenkes No 25/2016 dan Permensos No 5 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia).
Konteks untuk menjadikan Lansia sebagai subyek dalam upaya peningkatan kesejahteraannya tidak bisa lepas dari peran serta masyarakat. Peran masyarakat dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa, dan/atau fasilitas untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial (Pasal 52-53, PP No 39/2012). Untuk itu, implementasi dalam yang paling konkret berupa upaya mewujudkan Kawasan Ramah Lansia, sesuia dengan Permensos No 4/2017 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Ramah Lansia. Pasal 1 (3) menegaskan kawasan ramah Lanjut Usia sebagai wilayah dan masyarakat dengan fasilitas yang mendukung pemenuhan hak dan memfasilitasi kebutuhan Lanjut Usia.
Pemerintah, Pemerintah Provinsi/Kota/Kabuaten harus menyusun rencana strategi daerah Kawasan Ramah Lanjut Usia sebagai bagian dari dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam bentuk rencana pembangunan jangka menengah daerah. Dengan kriteria (Pasal 5) antara lain memiliki kebijakan kelanjutusiaan; perumahan-kawasan permukiman; ruang terbuka, bangunan dan transportasi yang ramah; penghormatan dan inklusi sosial; partisipasi sosial dan partisipasi sipil; pekerjaan yang ramah; dukungan komunitas dan pelayanan sosial; pelayanan kesehatan; layanan keagamaan dan mental spiritual; komunikasi dan informasi; advokasi sosial; bantuan hukum; dan/atau perlindungan Lanjut Usia dari ancaman dan tindak kekerasan. Oleh karenanya melibatkan Lansia berperan aktif dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya dan masyarakat menjadi penting (Pasal 10-f). Sehingga partisipasi sipil bisa berupa akses atas identitas, memiliki hak politik serta memungkinkan untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan (Pasal 12, Permensos No. 4/2017).
Dengan demikian, perencanaan pembangunan harus melibatkan kelompok Lansia sebagai subyek pembangunan. Kebijakan pembangunan perlu merangkul pendekatan inklusif yang melihat kelanjutusiaan sebagai elemen yang memperkaya pembangunan sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Ruang‐ruang itu sebenarnya sudah diberikan oleh berbagai instrumen hukum dan kebijakan pembangunan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah, Rencana Aksi HAM Nasional/Daerah, termasuk instrumen SDGs yang memberikan pijakan bagi Pemerintah untuk menghasilkan kebijakan berperspektik antargenerasi. Kewajiban ini diemban secara bersama‐sama, oleh Pemerintah Pusat dan terutama sekali, Pemerintah Daerah yang memikul tanggungjawab dalam hal peningkatan kualitas layanan dasar di daerahnya.
Bagian yang tak kalah penting, Pemerintah juga harus menyadari bahwa kelompok Lansia juga terdiri dari lapisan‐lapisan ekonomi, sosial, politik, dan kultural yang beragam mulai dari Lansia miskin hingga Lansia korban pelanggaran HAM masa lalu. Oleh karenanya, kebijakan ramah Lansia harus merepresentasikan kemajukan masalah serta komunitas Lansia sendiri. Karena diantara jumlah penduduk Lansia, ada sebagian dari mereka yang selama bertahun‐tahun mengalami diskriminasi sistemik, sebagai akibat dari perbedaan preferensi politik, etnisitas, ras, dan agama. Salah satunya adalah mereka para korban kekerasan masa lalu, yang terus mengalami stigmatisasi dan diskrimiasi, akibat perbedaan pilihan politik mereka di masa lalu. Diskriminasi sistemik adalah diskriminasi yang disebabkan oleh kebijakan‐kebijakan dan praktik‐praktik yang dibangun dalam sistem dan berdampak pada disisihkannya kelompok dan/atau menggiring kelompom tertentu ke peran dan posisi subordinat di dalam masyarakat.
Oleh karenanya kebijakan afirmasi akan menjadi perangkat penting, agar mereka mendapatkan hak dan layanan seperti halnya warga negara pada umumnya, guna mencapai keadilan. Sebagai contoh Jawa Tengah yang secara aktif mendorong Kota dan Kabupaten untuk mewujudkan kebijakan ramah Lansia. Mengingat di Jawa Tengah tercata penduduk Lansia mencapai 10 % atau sekitar 3,6 juta dari total penduduk dan dari jumlah tersebut, jumlah Lansia telantar atau berada di keluarga-keluarga miskin yang membutuhkan perhatian ekstra jumlahnya mencapai 125.951 orang (https://jatengprov.go.id/publik/dorong-perwujudan-provinsi-ramah-lansia/). Kebijakan perlakuan khusus bagi Lansia, yang didorong dari Pemerintah/Provinsi bagi Kota/Kabupaten juga telah dimandatkan lewat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan mengeluarkan Perda No. 6/2014 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.
Upaya agar Lansia bisa berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi, memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan. Dan memastikan Lansia memperoleh bantuan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial sebagai tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat, sesuai Pasal 5 (2) Perda Jateng No. 6/2014. Inisiasi tersebut bersamaan dengan agenda Kota/Kabupaten seperti Magelang yang mengeluarkan Perda No. 1/2015 tentang Lansia, Wonosobo No. 5/2016 tentang Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia, Karanganyar No. 13/2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia dan No. 4/2018 tentang Penyelenggaraan HAM. Termasuk Perwali Kota Surakarta No. 20/2018 tentang Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia dan Peraturan Daerah No. 4/2019 Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia. #KotaSolo #Lansia
Oleh Akhmad Ramdhon
Catat refleksi bersama Elsam Jakarta